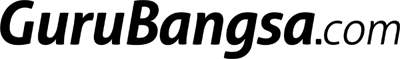Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
Pada tahun 1919, HOS Tjokroaminoto bertemu tiap hari Kamis siang di Kota Surabaya dengan dua saudara sepupunya. Mereka adalah KH M Hasjim As'yari dari Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan KH A Wahab Chasbullah.Tjokroaminoto disertai menantunya Soekarno, yang kemudian hari disebut Bung Karno.
Mereka mendiskusikan hubungan antara ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan/ nasionalisme. Terkadang hadir HM Djojosoegito, anak saudara sepupu keduanya, yang kemudian hari (tahun 1928) mendirikan Gerakan Ahmadiyah. Dari kenyataan-kenyataan di atas dapat dipahami mengapa Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926, selalu mempertahankan gerakan tersebut.
Di kemudian hari, seluruh gerakan Islam itu dimasukkan ke elemen gerakan yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah perkembangan sejarah. Ada generasi kedua dalam jajaran pendiri negeri kita, yaitu Kahar Muzakir dari PP Muhammadiyah, KH Abdul Wahid Hasyim dari NU, dan HM Djojosoegito (pendiri gerakan Ahmadiyah).
Tiga sepupu yang lahir di bawah generasi KH M Hasjim As'yari itu banyak jasanya bagi Indonesia. Mereka banyak mengisi kegiatan menuju kemerdekaan negeri kita. Setelah wafatnya Djojosoegito, muncul letupan keinginan membubarkan Ahmadiyah,tanpa mengenang jasajasa gerakan itu di atas. Padahal dalam jangka panjang,jasa-jasa itu akan diketahui masyarakat kita.
Dalam melakukan kegiatan,mereka tidak pernah kehilangan keyakinan. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan Indonesia merdeka.Karena itu,segala macam perbedaan pandangan dan kepentingan mereka disisihkan.Mereka mengarahkan tujuan bagi Indonesia. Mereka terus menjaga kesinambungan gerakan yang ada,guna memungkinkan lahirnya sebuah kekuatan yang terus menggelorakan perjuangan.
Hingga kemudian,NU melahirkan sebuah media pada 1928yangdinamai SoearaNU. Hal itu dilakukan guna memantapkan upaya yang ada.Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dipakai untuk kepentingan tersebut. Dalam nomor perdana majalah Soeara NU, KH Hasjim As'yari menyatakan bahwa ia menerima penggunaan rebana dan beduk untuk keperluan memanggil salat.
Namun, dia menolak penggunaan kentungan kayu. Menurutnya, penggunaan beduk dan rebana didasarkan pada sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.Sementara penggunaan kentungan kayu tidak ada dasarnya.Hal ini disanggah oleh orang kedua NU waktu itu, yaitu KH Faqih dari Pondok Pesantren Maskumambang di Gresik.
Hal itu dimuat sebagai artikel balasan dalam media "Soeara NU"edisi selanjutnya.KH Faqih menyatakan, "Apakah KH Hasyim lupa pada dasar pembentukan hukum dalam NU, yaitu Alquran,hadis, ijmak,dan qiyas?" Segera setelah itu, KH Hasyim As'yari mengumpulkan para ulama dan santri senior di Masjid Tebuireng.
Dia menyuruh dibacakan dua artikel di atas.Kemudian, dia mengatakan, mereka boleh menggunakan pendapat dari KH Faqih Maskumambang asalkan kentungan tidak dipakai di Masjid Pondok Pesantren Tebuireng itu. Terlihat di sini betapa antara para ulama NU itu terdapat sikap saling menghormati meski berbeda pendirian.
Hal inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan nyata. Penerimaan akan perbedaan pandangan sudah berjalan semenjak Fahien memulai pengamatannya atas masyarakat Budha di Sriwijaya dalam abad ke-6. Prinsip ini masih terus berlanjut hingga sekarang di negeri kita dan hingga masa yang akan datang. Sudah pasti kemerdekaan kita harus dilaksanakan dengan bijaksana dan justru digunakan untuk lebih mengokohkan perdamaian dunia.
Karena itu, diperlukan kemampuan meletakkan perdamaian dalam penyusunan politik luar negeri,yang diiringi dengan tujuan memperjuangkan kepentingan bersama. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan.
Bukankah kekuatan kita sebagai bangsa terletak dalam keberagaman yang kita miliki? Marilahkitabangunbangsadankita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.
Sumber: Seputar Indonesia , Selasa 21 April 2009
Read More
Pada tahun 1919, HOS Tjokroaminoto bertemu tiap hari Kamis siang di Kota Surabaya dengan dua saudara sepupunya. Mereka adalah KH M Hasjim As'yari dari Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang dan KH A Wahab Chasbullah.Tjokroaminoto disertai menantunya Soekarno, yang kemudian hari disebut Bung Karno.
Mereka mendiskusikan hubungan antara ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan/ nasionalisme. Terkadang hadir HM Djojosoegito, anak saudara sepupu keduanya, yang kemudian hari (tahun 1928) mendirikan Gerakan Ahmadiyah. Dari kenyataan-kenyataan di atas dapat dipahami mengapa Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926, selalu mempertahankan gerakan tersebut.
Di kemudian hari, seluruh gerakan Islam itu dimasukkan ke elemen gerakan yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah perkembangan sejarah. Ada generasi kedua dalam jajaran pendiri negeri kita, yaitu Kahar Muzakir dari PP Muhammadiyah, KH Abdul Wahid Hasyim dari NU, dan HM Djojosoegito (pendiri gerakan Ahmadiyah).
Tiga sepupu yang lahir di bawah generasi KH M Hasjim As'yari itu banyak jasanya bagi Indonesia. Mereka banyak mengisi kegiatan menuju kemerdekaan negeri kita. Setelah wafatnya Djojosoegito, muncul letupan keinginan membubarkan Ahmadiyah,tanpa mengenang jasajasa gerakan itu di atas. Padahal dalam jangka panjang,jasa-jasa itu akan diketahui masyarakat kita.
Dalam melakukan kegiatan,mereka tidak pernah kehilangan keyakinan. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan Indonesia merdeka.Karena itu,segala macam perbedaan pandangan dan kepentingan mereka disisihkan.Mereka mengarahkan tujuan bagi Indonesia. Mereka terus menjaga kesinambungan gerakan yang ada,guna memungkinkan lahirnya sebuah kekuatan yang terus menggelorakan perjuangan.
Hingga kemudian,NU melahirkan sebuah media pada 1928yangdinamai SoearaNU. Hal itu dilakukan guna memantapkan upaya yang ada.Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dipakai untuk kepentingan tersebut. Dalam nomor perdana majalah Soeara NU, KH Hasjim As'yari menyatakan bahwa ia menerima penggunaan rebana dan beduk untuk keperluan memanggil salat.
Namun, dia menolak penggunaan kentungan kayu. Menurutnya, penggunaan beduk dan rebana didasarkan pada sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.Sementara penggunaan kentungan kayu tidak ada dasarnya.Hal ini disanggah oleh orang kedua NU waktu itu, yaitu KH Faqih dari Pondok Pesantren Maskumambang di Gresik.
Hal itu dimuat sebagai artikel balasan dalam media "Soeara NU"edisi selanjutnya.KH Faqih menyatakan, "Apakah KH Hasyim lupa pada dasar pembentukan hukum dalam NU, yaitu Alquran,hadis, ijmak,dan qiyas?" Segera setelah itu, KH Hasyim As'yari mengumpulkan para ulama dan santri senior di Masjid Tebuireng.
Dia menyuruh dibacakan dua artikel di atas.Kemudian, dia mengatakan, mereka boleh menggunakan pendapat dari KH Faqih Maskumambang asalkan kentungan tidak dipakai di Masjid Pondok Pesantren Tebuireng itu. Terlihat di sini betapa antara para ulama NU itu terdapat sikap saling menghormati meski berbeda pendirian.
Hal inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan nyata. Penerimaan akan perbedaan pandangan sudah berjalan semenjak Fahien memulai pengamatannya atas masyarakat Budha di Sriwijaya dalam abad ke-6. Prinsip ini masih terus berlanjut hingga sekarang di negeri kita dan hingga masa yang akan datang. Sudah pasti kemerdekaan kita harus dilaksanakan dengan bijaksana dan justru digunakan untuk lebih mengokohkan perdamaian dunia.
Karena itu, diperlukan kemampuan meletakkan perdamaian dalam penyusunan politik luar negeri,yang diiringi dengan tujuan memperjuangkan kepentingan bersama. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan.
Bukankah kekuatan kita sebagai bangsa terletak dalam keberagaman yang kita miliki? Marilahkitabangunbangsadankita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali.
Sumber: Seputar Indonesia , Selasa 21 April 2009